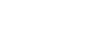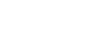-

Suasana subuh yang dramatis tertutup kabut di Wae Rebo

Vernacular architectural selalu menjadi perhatian arsitek Yori Antar sedari lama. Ziarah arsitektur ke berbagai belahan dunia kerap dilakoni bersama kelompok arsitek lain sebagai langkah pengisian energi dan ilmu baru sebagai perencana arsitek. Namun setelah berkeliling dunia, kekagumannya selalu kembali ke kekayaan arsitektur tradisional Tanah Air yang sangat luar biasa. Mencari dan menemukan local genius, sebuah istilah yang diungkapnya bersama kelompok kawan-kawan arsitek, merupakan kegiatan penting yang dijadwalkan setiap tahun untuk menjelajahi tempat-tempat tak tersentuh di seluruh Indonesia.
Suatu momen di tahun 2008, sebuah desa kuno Wae Rebo di Flores ditemukannya secara tidak sengaja, membuat Yori berusaha menemukan sebuah “harta karun arsitektur”. Ia dan teman-temannya ternyata menjadi pendatang Indonesia pertama di sana serta merasa penasaran karena menemui arsitektur yang berbeda di Flores. Saat tiba di sana pertama kali, setelah mendaki selama hampir 5 jam dengan berjalan kaki, Yori dan teman-teman menemukan serombongan mahasiswa Taiwan sedang melakukan program pertukaran desa adat dan sedang membantu perbaikan atap rumah-rumah di sana. Setiap tahun tercatat ada 80-100 orang asing yang datang ke Wae Rebo. Ketika mereka pulang saat itu, masuk lagi 15 turis asal Spanyol. Dengan kata lain, desa terpencil Wae Rebo saat itu telah mendunia tanpa dikenal oleh bangsanya sendiri!
Kondisi yang mengejutkan ini memecut Yori untuk melakukan sesuatu lebih dari sekadar sebagai turis. Sebagai turis, rampung membuat foto-foto yang indah lalu bisa langsung pulang tanpa berbuat apapun untuk masyarakat di sana. Yori merasa ingin berbuat lebih. Menemukan bentuk rumah adat yang terbuat dari konstruksi dari bambu, rotan dan kayu worok yang tersisa karena termakan usia membuat Yori dan kelompok arsiteknya tidak mau tinggal diam. Di sana, jumlah rumah adat yang disebut Mbaru Niang hanya terdapat 7 bangunan dan sesuai adat, jumlah itu tidak boleh bertambah. Namun yang keadaannya masih layak pakai hanya 2 yang tersisa. Maka dengan meminta izin dan restu ketua adat, dimulailah program perbaikan rumah adat di Wae Rebo dengan bantuan dana sejumlah para donatur lokal yang diwujudkan lewat program Rumah Asuh. Melihat bahwa rumah itu bukanlah sekadar bangunan fisik semata, namun merupakan simbol kesatuan antar keluarga dan masyarakatnya yang mewadahi budaya yang senantiasa hidup berkembang. Kondisi kemiskinan yang sempat membelit masyarakat di sana, mengakibatkan rumah-rumah itu termakan usia menuju kepunahan. Sebagai arsitek, Yori terpanggil untuk melestarikan rumah-rumah adat itu dari kematian.
Para penduduk desanya adalah penjaga budaya leluhur mereka yang secara turun-temurun mewarisi kepiawaian membangun rumah-rumah mereka. Karena itu proyek Rumah Asuh yang dilaksanakan Yori masih berpegang teguh pada teknik tradisional menggunakan sistem umpak, bebat, pasak tanpa paku dan memiliki ketahanan anti gempa. Yori menemukan DNA arsitektur Nusantara: pembangunan rumah adat dilaksanakan secara bergotong-royong dengan mengutamakan adat istiadat masyarakat setempat. Satu hal unik yang ditemukan Yori dari pengalamannya di sana adalah bagaimana sebuah pembangunan rumah adat dilakukan bukan dengan mengusai berbagai tahapnya dari buku, melainkan melalui penyampaian secara lisan dari generasi ke generasi berikutnya. Formula yang ditemukan Yori ini menunjukkan bahwa sejatinya arsitektur yang dipelajari di perguruan tinggi adalah melalui tulisan merupakan pola pemikiran Barat. Pola pengajaran Western adalah bersifat industrial dan modern yang melalui proses top down. Bertolak belakang dengan proses pembangunan arsitektur tradisional bersifat bottom up. Ironi ini menjadi pencerahan bagi Yori sebagai arsitek dan menjadikannya titik balik dalam melakukan preservasi rumah-rumah adat lainnya di wilayah Nusantara.
Preservasi dilakukan berkelanjutan hingga 2011 dan pada tahun 2013 yang tanpa dinyana kemudian membawa Yori menerima penghargaan Aga Khan Award untuk preservasi rumah adat Mbaru Niang dan penghargaan UNESCO untuk pelestarian budaya. Partisipasi mahasiswa dan sesama arsitek yang bahu-membahu melaksanakan proyek ini membawa Wae Rebo kini menjadi sebuah desa yang memiliki potensi pariwisata ekologi atau ecotourism. Masalahnya, mempertahankan keluhuran nilai tradisional yang ada sejak awal di sana merupakan langkah yang harus secara hati-hati dilakukan.
Kekhawatiran Yori akan perkembangan Wae Rebo yang mulai diarahkan ke mass tourism sebenarnya cukup beralasan. Perjalanan menuju desa terpencil yang harus ditempuh dengan mendaki selama 5 jam tanpa kendaraan merupakan inti dari pariwisata ekologi yang sangat menghargai alam sekitar. Bila nanti ada rencana untuk membuat jalan beraspal menuju ke sana, Yori dapat membayangkan perubahan drastis wajah Wae Rebo. Di desa, pendatang akan tinggal di dalam rumah penduduk dan menyaksikan kegiatan menenun kain hingga bercocok tanam. Para turis dan pendatang menikmati sajian hidangan yang dimasak penduduk asli. Hasil bumi Wae Rebo antara lain kopi yang sudah dikirimkan ke daerah lain seperti Bandung, Jawa Barat. Penghidupan masyarakatnya berangsur-angsur membaik dan ini merupakan contoh ecotourism yang sukses.
Menurut Yori, isu green building yang didengungkan di dunia Barat belakangan ini tak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh kekayaan budaya kita sendiri, khususnya di Wae Rebo. Cara berpikir kita sebagai orang Indonesia seperti dipelintir karena isu green building seolah-olah hanya bersumber dari dunia Barat. Padahal sebenarnya di banyak desa tradisional di negara kita sendiri, termasuk di Wae Rebo,yang dapat dipelajari berdasarkan kearifan tradisional yang sangat menghormati alam. Dengan mengangkat eco-tourism yang melandaskan hal-hal seperti inilah membuat kegiatan pariwisata memiliki nilai yang berbeda.
Foto: Dok. Yori Antar & Budi Surachmat
-